- Data Sawit Watch 2019, luas tutupan sawit mencapai 22,34 juta hektar tersebar di 22 provinsi dengan 90% berada di Sumatera dan Kalimantan. Luas lahan yang mencapai 1,2 kali Pulau Jawa itu menimbulkan konflik sosial, 52% dari 1.052 kasus merupakan konflik tenurial antara perusahaan sawit dan komunitas.
- Abdul Haris Semendawai, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengatakan, sengketa agraria di Indonesia sudah kritis. Konflik begitu banyak dan berkepanjangan berujung konflik sosial terbuka yang membawa korban jiwa dan harta benda. Hal lain, katanya, dalam konflik terjadi pelanggaran HAM.
- Kajian The Indonesia Bussines Council for Sustainable Development (IBCSD) 2016 menyebutkan, biaya perusahaan yang timbul dari konflik sosial mencapai US$70.000-US$2.500.000, atau sebesar 51%-88% dari biaya operasional perusahaan. Sementinya, perusahaan jadi pihak pendorong kuat penyelesaian konflik lahan, antara lain guna menekan biaya operasional.
- Penting ada penataan ulang mengenai pemilikan dan penggunaan atas tanah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan daya dukung ekologi dan populasi penduduk serta mencegah timbul konflik agraria baru.
Organisasi masyarakat sipil dan akademisi mendesak pemerintah segera menjalankan komitmen dalam penyelesaian konflik agraria, antara lain di perkebunan sawit. Kasus-kasus perampasan lahan masyarakat terus terjadi di tengah pemerintah getol membuka keran investasi.
Dalam tataran global, industri sawit erat kaitan dengan isu deforestasi, buruh anak, kebakaran hutan dan lahan, dan konflik sosial sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Data resmi pemerintah, rilis 2019, menyebutkan, luas tutupan sawit nasional 16.381.959 hektar. Sedangkan, data Sawit Watch 2019, luas tutupan sawit mencapai 22,34 juta hektar tersebar di 22 provinsi dengan 90% berada di Sumatera dan Kalimantan.
Luas lahan yang mencapai 1,2 kali Pulau Jawa itu menimbulkan konflik sosial, 52% dari 1.052 kasus merupakan konflik tenurial antara perusahaan sawit dan komunitas.
Abdul Haris Semendawai, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengatakan, sengketa agraria di Indonesia sudah kritis. Konflik begitu banyak dan berkepanjangan berujung konflik sosial terbuka yang membawa korban jiwa dan harta benda. Hal lain, katanya, dalam konflik terjadi pelanggaran HAM.
Pemerintah sudah coba membenahi tata kelola kebun sawit, antara lain, lewat Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Niatnya, regulasi ini memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dengan ada poin evaluasi perizinan sawit, dan sekaligus penyelesaian konflik agraria.

Dalam upaya penyelesaian konflik lewat skema reforma agraria ini, Kantor Staf Presiden membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). Tugasnya, akselerasi kementerian dan lembaga dalam menangani konflik-konflik agraria dan sumber daya alam.
Pada 2018, TPPKA menghimpun laporan konflik agraria dan sumber daya alam yang masuk melaluai KSP ada 555 kasus dengan luas 627.430,042 hektar, melibatkan 106.803 keluarga. Ia terdiri dari 306 kasus perkebunan (341.237,87 hektar), 163 kehutanan (246.746,73 hektar), 33 bangunan (2.259,936 hektar), infrastruktur 19 (2.288,536 hektar).
Kemudian, transmigrasi 17 kasus (6.952 hektar) dan kasus lain ada 17 seluas 27.944,97 hektar. Luas konflik agraria didampingi Walhi di 20 provinsi tercatat 487.595,42 hektar melibatkan 58.094 jiwa.
“Komitmen dari Presiden Jokowi (Joko Widodo-red) sudah ada, tapi bagaimana komitmen itu bisa direalisasikan,” katanya.
Kajian akademik, kata Abdul, menunjukkan sengketa maupun konflik agraria memiliki akar dan dimensi yang kompleks. Sengketa karena berbagai faktor termasuk pengakuan hak adat atau ulayat lemah dalam kontruk hukum di Indonesia, tumpang tindih perizinan dan alokasi kawasan, pendudukan atau perampasan kawasan, korupsi, perilaku ekspansif dari berbagai aktor. Baik itu, perusahaan, mafia lahan, dan para spekulan tanah—termasuk relatif rendahnya kinerja pemerintah dalam merespon dan menyelesaikan konflik dengan berbagai mekanisme.
”Perlu ada konsesus nasional dalam menyelesaikan kasus-kasus agraria dengan mengedepankan prinsip HAM,” katanya.
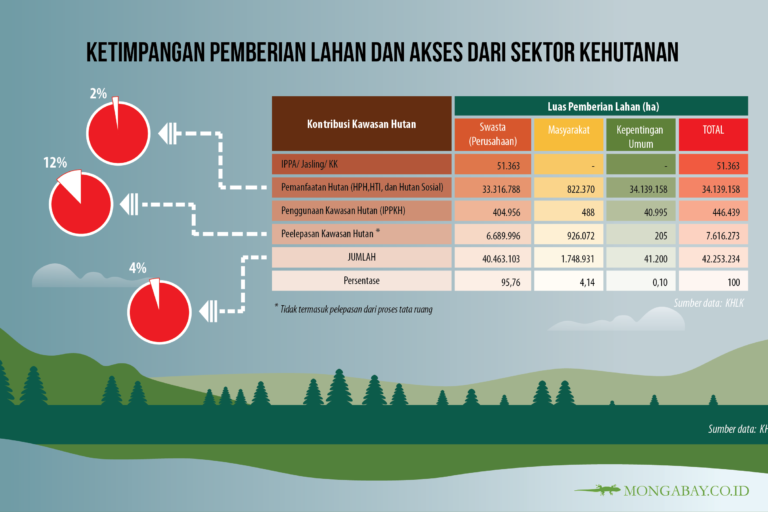
Dia bilang, penyelesaian konflik agraria ini mendesak, perlu ada kesepakatan dan kerja sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Juga perlu kesepakaran terkait indikator penyelesaian konflik agraria.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria, perlu ada kesamaan pandangan untuk pengakuan dari aktor yang terlibat, antara negara, masyarakat dan swasta. “Dengan ada pengabaian salah satu aktor bisa menyebabkan penyelesaian tidak efektif.”
Sebenarnya pemerintah, dalam TAP MPR IX 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyadari ada masalah ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi ini menyebakan konflik dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumber daya alam.
Sayangnya, kata Yaya, biasa disapa, hingga kini tidak ada komitmen serius pemerintah menyelesaikan konflik ini.
“Selama ini keinginan penyelesaian konflik agraria serius terlihat dari masyarakat.”
Padahal, katanya, konflik merugikan para pihak. Konflik bagi perusahaan, katanya, menyebabkan biaya tinggi. Lagi-lagi, tidak terlihat komitmen pemerintah serius menyelesaikan.
Konflik, naikkan biaya operasional
Kajian The Indonesia Bussines Council for Sustainable Development (IBCSD) 2016 menyebutkan, biaya yang timbul dari konflik sosial mencapai US$70.000-US$2.500.000, atau sebesar 51%-88% dari biaya operasional perusahaan.
“Perusahaan seharusnya memiliki interest dalam penyelesaian konflik sosial dan agraria, tapi kenapa tidak kelihatan selama ini perusahaan menginginkan menyelesaikan konflik?”
Imam A. El Marzuq, Senior Manager Global Community Outreach & Engagement RSPO Indonesia mengakui ada peningkatan pengaduan konflik sawit di Indonesia dari waktu ke waktu.
Kondisi ini, kata Imam, karena faktor luar seperti ekspansi di Indonesia masih terjadi. “Ekspansi menimbulkan masalah-masalah baru yang muncul dari aspek sosial dan lingkungan.”

Selanjutnya, ada ketidakseimbangan posisi antara masyarakat lokal atau adat dengan perusahaan perkebunan, sampai hukum tumpang tindih.
Peran advokasi dari LSM cukup penting, katanya, demokrasi dan keterbukaan menyediakan lingkungan lebih baik bagi masyarakat; . Juga ada mekanime alternatif penyelesaian konflik.
Secara global, berdasarkan data RSPO sejak 2009 sampai 30 Juni 2020, ada 147 pengaduan masuk dan 107 sudah selesai tutup. “Dari 147 kasus masuk ke RSPO, 63% dari Indonesia,”kata Imam.
Dia bilang, keluhan paling banyak masuk terkait isu hak atas tanah dan FPIC, diikuti isu lingkungan dan orangutan, penggunaan tanah, hak pekerja, skema kemitraan dan transparansi perusahaan.
Lembaga khusus
Yaya mengusulkan perlu institusi khusus di bawa presiden yang bekerja penyelesaian konflik agraria. “Ini jadi kerangka reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria struktural, bukan upaya yang hanya bussines as usual.”
Dia minta, pemerintah tak lagi beri atau perpanjang izin guna memotong ÷perpanjangan konflik lama yang harus selesai. dengan ada izin baru dan perpanjangan izin bisa jadi sumber konflik baru.
Terpenting juga, katanya, pengakuan dan perlindungan lahan masyarakat dan proses pelepasan eks HGU kepada masyarakat.
“Mekanisme pasar juga bisa ditempatkan sebagai suplemen dari penyelesaian konflik agraria oleh negara.”
Namun, Yaya khawatir, upaya memutus rantai konflik agraria ini terjegal dengan ada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law). Semangat RUU ini sangat kontradiktif dengan agenda penyelesaian konflik agraria.
Abdul juga bilang, perlu ada pengadilan khusus pertanahan. “Pengadilan tidak hanya terpaku terhadap alas hak, tetapi mampu menelaah segala faktor yang melatarbelakangi terjadi konflik, ditinjau dari aspek historis, kepentingan dan lain-lain.” Dengan begitum katanya, dapat menghasilkan suatu penyelesaian konflik yang berkeadilan.
Dia berharap, RUU Pertanahan mampu jadi mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik agraria struktural bukan sebaliknya.
“Penyelesaian konflik harus dibarengi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai selama kejadian konflik.”
Penting juga, katanya, ada penataan ulang mengenai pemilikan dan penggunaan atas tanah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan daya dukung ekologi dan populasi penduduk serta mencegah timbul konflik agraria baru.
Keterangan foto utama: Masyarakat adat di Sorong Selatan, yang berkonflik dengan perusahaan sawit. Foto: Pemuda Mahasiswa Iwaro/Mongabay Indonesia








