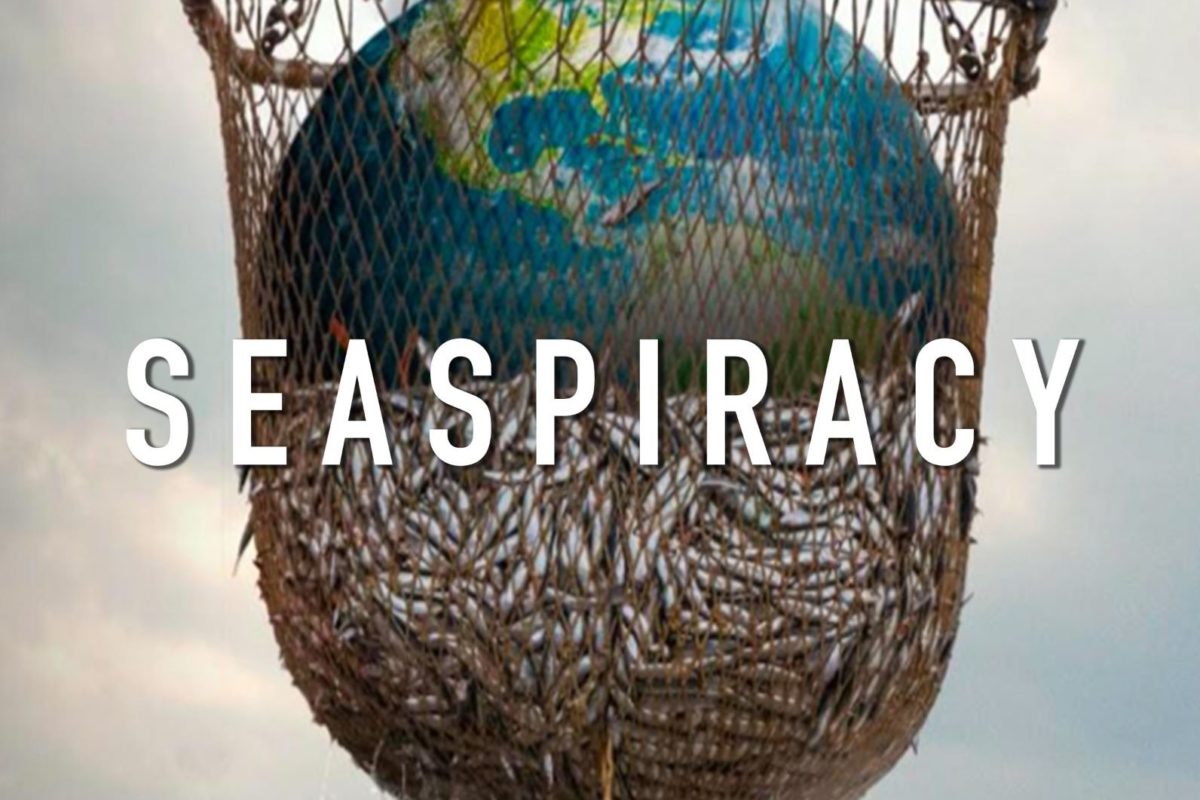“I finally understood sustainability.
It just meant that something could continue
on and on forever regardless of how much suffering it caused.”
Ali Tabrizi
Sama dengan jutaan anak di seluruh dunia, Ali Tabrizi tumbuh dengan menyaksikan acara-acara yang mengangkat keindahan lingkungan yang dibawakan oleh Jacques Cousteau, David Attenborough dan Sylvia Earle. Tabrizi kemudian memupuk kecintaan pada lingkungan, dan terlibat aktif dalam beragam gerakan untuk menjaga lingkungan.
Akhirnya, mengikuti jejak para pahlawannya semasa kecil, di umur 22 tahun ia memutuskan untuk mulai membuat film tentang bagian lingkungan yang sangat ia cintai: lautan. Demikian yang ia sampaikan di bagian awal film dokumenter Seaspiracy yang ia buat.
Tetapi, berbeda dengan tujuan semula, ketika ia mulai melakukan riset tentang lautan sebagai bahan dasar untuk filmnya, rangkaian kabar buruklah yang ia temukan. Paus terdampar di pantai dengan tiga puluh tas plastik di dalam perutnya. Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah plastik seberat 150 juta ton yang terus terombang-ambing di lautan. Laut tercemar mikroplastik. Dan seterusnya.
Ia kemudian menjadi lebih giat memunguti sampah-sampah di pantai, dan berdonasi ke gerakan-gerakan yang memiliki perhatian yang sama. Sampai akhirnya ia bangun di suatu pagi mendengarkan bahwa Jepang memutuskan untuk kembali melakukan perburuan paus untuk kepentingan komersial, yang sesungguhnya telah dilarang dilakukan sejak 1986.
Bersama istrinya yang sangat suportif, Lucy Tabrizi, mereka kemudian bertolak ke Jepang. Mereka menuju ke tempat bernama Taiji, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana sesungguhnya perburuan paus itu dilakukan, serta untuk mewawancarai Ric O’Barry yang sudah lama mendalami isu ini. Wawancara berhasil dilakukan, namun mendekati lokasi yang mereka ingin lihat itu sama sekali tidak mudah. Dan, ternyata di Taiji mereka menemukan bahwa bukan hanya paus yang diburu, melainkan juga lumba-lumba.
baca : Perdagangan Hiu : Pasar Memicu Kepunahan (3)
Sama dengan banyak film dokumenter lainnya yang bertutur tentang isu-isu yang sensitif dan menyerempet bahaya, Seaspiracy menunjukkan itu. “When you first show up in Taiji, immediately, the police are on you. They’re at your hotel. They’re following you everywhere you go. You got the Yakuza, you got the right wing, you got the government, the fishermen, you got everybody against you. The room is bugged, the telephone is bugged. The television is actually photographing you while you’re in your room.” Begitu keterangan O’Barry. Dan betul saja, adegan-adegan berikutnya menunjukkan mereka dicegat dan ditanyai oleh polisi setempat. Kamar hotel mereka diawasi, dan seterusnya.
Setelah mendapati beberapa kesulitan di Taiji, mereka melongok ke sebuah pelabuhan yang jaraknya sepelemparan batu, dan mendapati sebuah industri bluefin tuna, ikan termahal di dunia. Bersama-sama dengan tuna yang lain, industri ini membentuk pasar USD42 miliar per tahun. Dan, perburuan dan pembantaian atas lumba-lumba yang terjadi di dekatnya merupakan dalih atas apa yang sebenarnya terjadi: pengambilan ikan yang berlebih, alias overfishing. Industri ini tak mau disalahkan atas makin sulitnya tuna diperoleh, dan membuat kambing hitam. Makhluk manis itu dibantai karena memang memakan ikan yang menjadi konsumsi manusia, dan bisa menutupi kejahatan industri.
Setelah gagal mendapatkan penyataan dari perusahaan tuna terbesar di dunia yang dimiliki oleh Mitsubishi, mereka kemudian kembali menampilkan rekaman spesies lainnya yang banyak ditemukan di pelabuhan itu: hiu. Hiu-hiu ditangkap, dipotong siripnya, dan dibuang lagi ke lautan. Memang, hanya siripnya saja yang dikonsumsi. Mereka juga menunjukkan bahwa mendapatkan informasi tentang praktik terkait produk ini, lebih sulit lagi. Kali ini, yang mereka hadapi adalah preman, dan mereka diusir ketika memfilmkannya.
Pasangan itu lalu pergi ke Hong Kong, untuk mendapatkan informasi lebih jauh dari tempat di mana sirip hiu paling banyak dikonsumsi. Ceritanya serupa, mereka sulit untuk mendapatkan informasi langsung dan terbuka. Mereka menggunakan kamera tersembunyi untuk bisa merekam bermacam kondisi terkait industri ini, terutama yang sudah dekat dengan konsumsi. Dan merekapun bicara kepada pakar. Kali ini dengan Paul de Gelder, Profesor Callum Roberts, Guy Stokes yang bisa menjelaskan dengan sangat apik apa permasalahan terkait dengan hiu.
“People should not be afraid of having sharks in the ocean. They should be afraid of not having sharks in the ocean. The sharks keep the oceans healthy. They keep the fish stocks healthy. They keep the ecosystems alive. They keep the coral reefs alive. If we don’t have these sharks, if these sharks get finned into extinction, the ocean’s gonna turn into a swamp. And guess who’s gonna die next? Us.” Begitu kata de Gelder.
Roberts juga bicara tentang peran penting predator, namun Stokes-lah yang menerangkan dengan sangat baik kaitan antara beragam jenjang rantai makanan dengan kesehatan lingkungan. Lalu, Stokes juga menyatakan hal yang mustahil dilupakan: “Around the world, on average, sharks kill about ten people per year. Now, comparatively speaking, we kill 11,000 to 30,000 sharks per hour. The crazy thing is, almost half of those sharks killed are killed as bycatch from commercial fishing fleets. And they’re discarded as waste back into the ocean.”
baca juga : Perdagangan Hiu Marak di TPI Brondong, Berikut Foto-fotonya
Dari sini pembicaraan mulai menjadi tegas, bahwa industri perikanan laut adalah isu terbesarnya, atau, menggunakan pelesetan perumpamaan yang sangat popular, industri perikanan laut adalah whale in the room. Bycatch, atau tangkapan ikutan, dinyatakan membunuh setidaknya 50 juta hiu per tahun. Dan hiu hanyalah sedikit di antara tangkapan ikutan yang dalam film ini disebutkan meliputi 40% dari total tangkapan. Paus, lumba-lumba, anjing laut, penyu dan spesies burung laut adalah di antara beragam tangkapan ikutan itu.
Buat mereka yang memiliki kesadaran akan hal ini, biasanya akan dengan sangat hati-hati memilih jenis hidangan laut apa yang dipilih, di antaranya dengan menyandarkan diri pada label yang diberikan dari organisasi semacam Marine Stewardship Council (MSC) dan Earth Island Institute.
Film ini lalu memberikan kabar buruk, yaitu bahwa label-label seperti itu sesungguhnya tak bisa dipercaya. Ali Tabrizi menunjukkan bahwa bukan saja permintaan untuk wawancaranya ditolak oleh MSC dan wawancara dengan Earth Island Institute tampak sedemikian tidak meyakinkannya, ia juga mengungkap apa yang menurut dia sebagai praktik yang penuh konflik kepentingan, yaitu bahwa perusahaan-perusahaan-lah yang membayar untuk memperoleh label-label ‘ramah lingkungan’ itu.
Tabrizi juga keheranan menemukan bahwa organisasi-organisasi yang melalukan kampanye terkait sampah plastik di lautan tampak seperti enggan menunjuk hidung perusahaan-perusahan perikanan laut. Alih-alih bicara tentang bekas jala raksasa yang sangat tinggi persentasenya di Great Pacific Garbage Patch, banyak kampanye malah menunjuk sedotan plastik sebagai isu. Tabrizi jelas sekali hendak menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang tampak hendak menyelamatkan kehidupan di lautan itu tak becus atau bahkan sengaja mengalihkan isu.
perlu dibaca : Kawasan Samudera Pasifik yang Dipenuhi Sampah Plastik kini Hampir Seluas Daratan Indonesia
Lalu, pada titik tersebut, Profesor Callum Roberts kembali muncul dengan pernyataan yang sangat kuat. “The Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico was the biggest in history. It gushed huge quantities of oil into the deep sea for a period of months. And everyone was appalled at the death of wildlife on the beaches as the oil slopped ashore. But in fact, the fishing industry in the Gulf of Mexico destroyed more animals in a day than that oil spill did in months. Because large areas were closed to fishing because of the possibility of being tainted by oil, marine life actually benefited from the Deepwater Horizon oil spill because it got a respite from fishing.” Bayangkan saja, kehidupan laut itu lebih baik ditumpahi minyak sebanyak itu dibandingkan menanggung akibat dari perikanan komersial!
Film ini kemudian bergerak menjelaskan bagaimana terumbu karang hancur lantaran praktik penangkapan ikan dengan alat tangkap raksasa. Sylvia Earle, pahlawan masa kecil Tabrizi bicara pada segmen ini bersama dengan Profesor Chris Langdon dan Cyrill Gutsch. Terumbu karang adalah rumah dan sumber pangan bagi ikan, dan penghancurannya jelas akan membuat ikan-ikan menjadi gelandangan dan menderita kelaparan, lalu mati. Di sini juga Tabrizi juga sampai pada kesimpulan terbesar di film ini, yaitu bahwa tidak ada yang namanya perikanan laut berkelanjutan.
Dari situ, Tabrizi terus bergerak memberikan informasi yang mendukung klaimnya. European Commissioner of Fisheries and the Environment ia datangi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Diskusi tentang MSC muncul kembali. Peran subsidi Uni Eropa yang membuat para nelayan di Afrika Barat mustahil berkompetisi dengan perikanan komersial raksasa menyusul kemudian. Bajak laut Somalia, dijelaskan Tabrizi, tadinya adalah para nelayan yang kemudian kehilangan kemampuan memberi makan keluarganya lantaran perikanan komersial dari Eropa. Perampokan sumber daya perikanan di Afrika Barat juga disebutkan sebagai kontributor munculnya wabah Ebola.
Tabrizi kemudian loncat ke Skotlandia, di mana perikanan budidaya salmon dilakukan. Kalau perikanan tangkap digambarkan sedemikian destruktif, apakah lalu perikanan budidaya merupakan jawabannya? Tidak juga. Bersama-sama dengan aktivis Don Staniford, Tabrizi mengungkap betapa budidaya salmon sesungguhnya juga memiliki segudang masalah. Mulai dari pencemaran hingga kondisi ikan yang tak sehat ia ungkap, hingga penggunaan pewarna pada pakan agar daging salmon benar-benar menarik mata konsumen. “This was the real monster in the lochs of Scotland,” begitu simpul Tabrizi.
baca juga : Tak Punya Salmon, Indonesia Ambisius Jadi Eksportir Olahan Salmon
Video dan gambar yang dipilih oleh Tabrizi selalu memberikan efek yang kuat. Musik dramatis yang dipilih menambah kekuatan gambarnya. Banyak infografis yang sangat efektif mendampingi narasi Tabrizi atau para narasumber yang diwawancarainya. Tabrizi juga jelas memilih alur filmnya dengan sangat hati-hati. Dia membangun pesannya dengan menempatkan isu-isu yang ‘ringan’ di bagian depan, lalu dibuat semakin berat ke belakang. Ia adalah penutur yang brilian, karena susunan itu berhasil membuat para penontonnya terus mengikuti apa yang hendak ia sampaikan di dokumenter sepanjang 89 menit ini. Dan Tabrizi jelas menyimpan argumentasinya yang terbaik di penghujung, untuk menikam benak dan hati siapapun yang menonton.
Ia kembali ke Asia, tepatnya ke Thailand, untuk menggambarkan kebrutalan kehidupan pekerja perikanan komersial di sana. Jam kerja yang panjang plus kondisi kerja yang buruk harus ditanggung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di atas kapal. Tapi itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan horor kekerasan hingga pembunuhan yang dituturkan para penyintas yang diwawancari Tabrizi.
Mereka bersaksi tentang penggunaan pekerja paksa dan pekerja anak, penggunaan batangan besi dan pistol untuk ‘mendisiplinkan’ pekerja, dan pembuangan mayat yang dibunuh ke laut, atau dimasukkan ke dalam freezer. Saking kerasnya kondisi itu, seorang narasumber menyatakan dia berpikir untuk bunuh diri sebanyak tiga kali dalam satu musim penangkapan. Mustahil untuk tidak merasa ngeri membayangkan situasi yang mereka hadapi.
Tetapi, membayangkan tentu tak sama dengan melihat. Untuk itu, Tabrizi menyajikan teror kepada penontonnya di bagian ujung. Ia pergi ke Faroe Islands, bagian dari Denmark, di Atlantik Utara. Di situ ada tradisi Grind, yang diklaim merupakan bentuk perburuan paus yang tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan, dengan spesies yang tak berstatus terancam. Setelah menunggu selama 10 hari di sana, kesempatan datang untuk menyaksikan Grind secara langsung di Hvannasund. Horor yang kemudian tampil benar-benar mustahil dilupakan. Adegan pembantaian, paus-paus yang mati, dan air laut yang berwarna darah bakal terus menghantui penonton.
Rasmussen, salah satu pelaku tradisi Grind, diwawancarai. Ia bertanya, apakah manusia yang membunuh 2000 ekor ayam lebih baik daripada mereka yang memilih membunuh satu paus? Perbandingan bobot daging dengan jumlah nyawa hewan yang harus diambil untuk menyediakan kebutuhan yang sama itu sangatlah dalam.
Ketika para penonton terhenyak dengan pertanyaan itu, Sylvia Earle kembali muncul. Ia bilang “To me, it’s remarkable that the question is even asked that, “Do fish feel pain?” As a scientist, it’s common sense. They have a nervous system, fish do. They have the basic elements that all vertebrates have. They have the capacity to feel on a level that I almost can’t imagine we can.” Ikan, dan mamalia laut, agaknya merasakan sakit yang lebih kuat daripada manusia ketika dibunuh.
perlu dibaca : Siapa Saja Para Pemburu Paus di Dunia?
Di sini pesan Tabrizi lengkap sudah. Perikanan laut tangkap dan budidaya tidaklah berkelanjutan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangatlah besar, dan label-label yang ada sesungguhnya hanya kedok dari praktik yang destruktif. Dan, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang hanya bisa dipenuhi dengan membunuh hewan yang merasakan kesakitan ketika nyawanya meregang. Pernyataan (sarkasme?) Tabrizi yang dikutip di bagian awal tulisan ini meringkas dengan sangat baik apa yang sedang terjadi. Jalan keluarnya? Berhenti makan hewan lautan. Begitu rekomendasi Tabrizi.
Simplifikasi yang berlebihan soal jalan keluar dari semua masalah ini adalah tumit Achilles dari film ini. Penggambaran yang menyeragamkan seluruh praktik perikanan tangkap juga jelas problematik. Ambisi Tabrizi untuk menjejalkan seluruh informasi ke dalam satu film, telah membuat banyak informasi bersifat selintasan. Jelas, ada banyak penonton yang mau belajar isu plastik di lautan dalam satu film utuh dengan lebih mendalam, juga soal penghancuran terumbu karang yang dinyatakan jauh lebih buruk daripada penggundulan hutan di Amazon, atau konflik kepentingan dalam label keberlanjutan, atau soal nasib anak buah kapal di kapal-kapal besar, juga soal tradisi Grind.
Kesan selintasan untuk setiap isu itu sedemikian kuat, walau jahitan Tabrizi tetap kuat. Dan, lantaran jejalan informasi yang ekstra-padat itu pulalah ada banyak upaya pengecekan yang menemukan bahwa apa yang disajikan Tabrizi tak seluruhnya akurat. Sebagai undangan kepada umat manusia agar tak lupa lautan, film ini jelas sangat berhasil. Tetapi menontonnya tetap memerlukan kritisisme yang sehat.
Ketika tulisan ini ditulis, bertepatan dengan Hari Bumi 2021, agregat nilai untuk film ini adalah 75%, menurut Rotten Tomatoes, situs IMDb memberikan nilai 8,3/10, dan 96% penonton menyatakan menyukainya. Jelas, ini adalah salah satu film dokumenter bertema lingkungan yang akan menjadi bahan diskusi hingga bertahun-tahun dari sekarang.
Para aktivis yang hendak mengritisi praktik buruk di industri ini jelas akan memanfaatkan dokumenter ini untuk kampanye, demikian pula dengan para aktivis vegetarianisme dan veganisme. Tabrizi, yang kini berusia 27 tahun, juga istrinya yang menjadi sinematografer dan editor, telah berhasil menempatkan diri dalam jajaran elit pembuat film dokumenter, dan karya-karya berikutnya pasti ditunggu oleh para penonton.
*Jalal, Reader on Corporate Governance and Political Ecology Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Artikel ini merupakan opini penulis