Rusaknya gambut dan mangrove di Indonesia bukan karena perubahan budaya pada masyarakat yang hidup di sekitar gambut dan mangrove. Tapi, dikarenakan berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia yang tidak bisa menjaga kelestariannya. Mulai dari hadirnya perusahaan HPH, transmigran, perkebunan sawit, pertambakan udang, hingga HTI.
Secara ekonomi, mungkin kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan bagi negara. Namun, dampaknya pun luar biasa, yang mungkin membutuhkan waktu panjang untuk memperbaikinya. Termasuk, kemungkinan banyak keragaman hayati yang hilang atau sulit dikembalikan lagi.
Berdasarkan penelusuran atau liputan saya terkait gambut dan mangrove di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, hingga Kepulauan Bangka-Belitung, dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan gambut dan mangrove bukan sebatas: krisis air bersih; bencana kabut asap; terlepasnya ribuan hingga jutaan ton karbon; terancam atau hilangnya flora dan fauna; kemiskinan pada masyarakat; serta, menurunnya kualitas kesehatan, terutama pada perempuan dan anak.
Tapi juga, mengancam dan menghilangkan komunitas adat; lahirnya generasi kriminal; lahirnya generasi ekstraktif; dan, rusak atau hilangnya situs sejarah [Melayu Tua dan Sriwijaya].
Baca: Lingkar Temu Kabupaten Lestari Targetkan Selamatkan Hutan dan Gambut

Rekulturisasi?
Selama ini, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove [BRGM] bekerja dengan skema 3R, yakni rewetting, revegetation, dan revitalization.
Dalam acara Bincang Gambut dan Diskusi Lanjutan Penyusunan Rencana Kegiatan yang digelar WikiGambut Sumatera Selatan secara daring, Jumat [09/7/2021], saya bersama Budi Wijaya, Kepala Balai Arkeologi [Balar] Sumatera Selatan, serta Ari Nurlia, peneliti dari Balai Litbang LHK Palembang, mencoba berbagi pengalaman dan gagasan terkait restorasi rawa gambut dan mangrove.
Saya menawarkan kiranya BRGM menambah skemanya. Bukan hanya 3R, tapi 4R. Yakni rewetting, revegetation, revitalization, dan reculturalization [rekulturalisasi]. Artinya, ditambah upaya restorasi budaya.
Mengapa?
Seperti dinyatakan di atas, kerusakan gambut dan mangrove juga mengancam dan menghilangkan komunitas adat. Di Sumatera Selatan, kerusakan gambut menghilangkan komunitas masyarakat lebak. Masyarakat yang selama ratusan tahun hidup di lebak [rawa gambut] yang mampu hidup dengan kondisi alami rawa gambut. Lalu, di Sumatera Selatan dan Jambi juga mengancam keberadaan Suku Anak Dalam [SAD] yang hidup di wilayah pesisir, termasuk juga suku melayu tua.
Di Kalimantan, kerusakan gambut membuat berbagai tradisi dan budaya sejumlah suku dayak menjadi hilang atau terancam.
Kerusakan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung, membuat sejumlah suku melayu kehilangan sumber ekonomi, dan terancam kehilangan sejumlah tradisinya.
Baca: Jika Hutan dan Lahan Terbakar, COVID-19 Kian Menyebar?

Lalu, lahirnya generasi kriminal. Di Sumatera Selatan, sejumlah wilayah yang rawa gambutnya rusak, menyebabkan sumber ekonomi hilang. Dampaknya, lahir generasi muda yang hidup dengan cara-cara negatif, seperti mencuri, merampok, atau bisnis narkoba.
Lebih parah lagi, muncul generasi ekstraktif atau generasi yang mencari pendapatan ekonomi dengan cara cepat tanpa mempertimbangkan lingkungan atau tidak peduli dengan lingkungan menjadi rusak atau tidak. Misalnya, para pemuda dari wilayah Sumatera Selatan yang rawa gambutnya rusak, merantau ke Jambi, Riau, Kalimantan, Bangka Belitung, untuk merambah hutan. Mencari kayu.
Setelah hutan habis, sebagian mereka kemudian melanjutkan aktivitas penambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Mereka menambang timah baik di darat maupun perairan.
Terakhir, rusaknya rawa gambut, juga berdampak rusak dan hilangnya berbagai situs sejarah terkait masyarakat melayu tua [pra Kedatuan Sriwijaya], masa Kedatuan Sriwijaya, hingga pasca-Kedatuan Sriwijaya di sepanjang Pesisir Timur Sumatera Selatan dan Jambi. Kerusakan ini baik karena lahan terbuka karena transmigran, perkebunan dan HTI, juga peristiwa kebakaran.
Situs-situs ini jumlahnya ratusan hingga ribuan. Demikian kata Budi Wijaya, dengan paparan berjudul “Gambut Dan Penelitian Arkeologi di Pantai Timur Sumsel”.
Situs yang terdapat di Karangagung Tengah [Kabupaten Musi Banyuasin], Air Sugihan [Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI], serta Tulung Selapan [Kabupaten OKI], menandakan di masa lalu ada kehidupan antara kelompok masyarakat dengan rawa gambut. Sebuah peradaban.
Pada situs-situs tersebut, ditemukan artefak yang terkait kehidupan [hutan] rawa gambut, misalnya tiang rumah panggung, perahu, damar, kerang, tempurung kelapa, buah nipah, serta satwa seperti monyet ekor panjang, lutung, babi liar, luwak, ular piton, biawak, kura-kura, ikan lele, ikan juaro, ikan lumajang, buaya, serta hiu air tawar.
Berdasarkan uraikan tersebut, tampaknya restorasi budaya [reculturalization] cukup penting dalam upaya kita melakukan restorasi gambut dan mangrove.
Asumsinya, percuma gambut dan mangrove kembali membaik, jika manusia yang hidup di sekitarnya tidak memiliki kesadaran atau kehilangan nilai-nilai luhur yang arif terhadap lingkungan.
Baca: Sebaiknya KKP Berperan pada Restorasi Gambut. Mengapa?
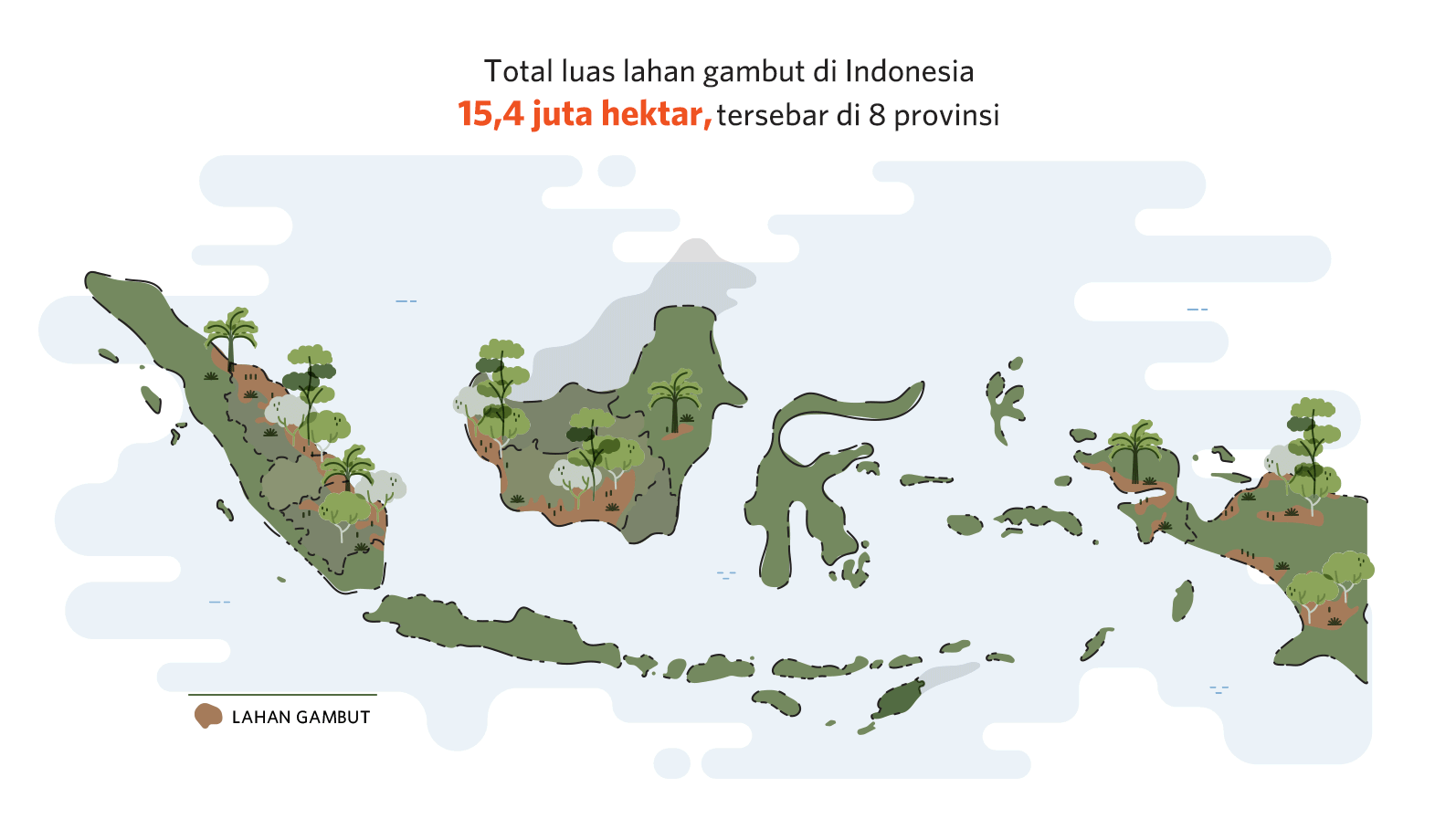
Seperti diketahui, jauh sebelum gambut dan mangrove di Indonesia rusak, masyarakat yang hidup di sekitarnya tumbuh dalam budaya yang arif terhadap lingkungan atau alam.
Kebudayaan yang dibangun dari kepercayaan atau keyakinan jika manusia bukan pusat kehidupan. Alam semesta yang menjadi pusat kehidupan [Ekosentrisme]. Berbagai tradisi dan budaya lahir dari keyakinan bahwa manusia dengan alam untuk saling menjaga dan memberi, yang selama ratusan tahun hidup sebagai adat [Deep Ecology].
Dalam budaya ini pun tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, dalam posisi tertentu perempuan yang sangat dimuliakan. Seperti menjadi dukun [ahli pengobatan]. Dan, tidak sedikit perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah komunitas.
Kekuatan adat ini mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi [kapital] dengan kelestarian alam, seperti di masa Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit; rakyat dan penguasa hidup makmur bersama alam yang terjaga.
Pandangan ini tercermin dari pernyataan Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya, di dalam Prasasti Talang Tuwo [684] bahwa alam [Taman Sri Ksetra] diperuntukan untuk semua makhluk hidup.
Saat ini, jejaknya terbaca dari falsafah masyarakat Minangkabau yang menyatakan “alam takambang menjadi guru”. Alam merupakan sumber pengetahuan bagi manusia untuk hidup berkelanjutan. Maka, jika alam rusak, manusia kehilangan gurunya. Alam harus dijaga.
Di Sumatera Selatan, gajah dan harimau secara adat tidak diburu atau dibunuh karena merupakan “saudara tua”. Di Kepulauan Bangka Belitung, hutan [termasuk mangrove] adalah jiwa manusia. Jika hutan habis, maka berakhir pula hidup manusia.
Baca: Tidak Lagi Terbakar, Dua Desa Ini Kembangkan Wisata Sejarah dan Ekowisata

Perempuan dan generasi muda
Menurut saya, ada dua kelompok sasaran utama dalam menjalankan rekulturalisasi yakni perempuan dan generasi muda.
Berdasarkan pengamatan saya, termasuk pandangan Ari Nurlia dari Balai Litbang LHK Palembang dengan paparan berjudul “Perempuan dan Gambut”, perempuan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar rawa gambut. Bisa berperan positif maupun negatif.
Artinya, perempuan dapat memanfaatkan rawa gambut secara positif menjadi sumber ekonomi, seperti memanfaatkan purun menjadi anyaman, ikan sebagai ikan asin atau ikan asap, atau memanfaatkan buahan hutan sebagai sumber makanan. Tapi, perempuan juga dapat menjadi pendorong para lelaki [suami dan anak] untuk merambah hutan atau melakukan pembakaran lahan guna kebutuhan ekonomi atau pertanian yang murah dan cepat.
Namun, posisi perempuan yang merupakan salah satu korban pertama dari kerusakan rawa gambut, justru keterlibatannya sangat rendah dalam program restorasi rawa gambut yang sudah berjalan. Dalam sejumlah kegiatan atau pertemuan terkait strategi mengatasi kebakaran hutan dan lahan, perempuan sangat minim terlibat.
Mereka hanya dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Seperti usaha kerajinan anyaman purun. Kegiatan ini lebih mengarah mengatasi persoalan ekonomi dibandingkan membangun nilai-nilai menjaga lingkungan.
Bukti yang saya temukan. Meskipun ekonomi perempuan pada sebuah wilayah meningkat dengan berkembangnya sebuah usaha, ternyata kebakaran rawa gambut terus terjadi setiap tahun.
Beranjak dari hal tersebut, menurut saya, perempuan harus berada di depan dalam menjalankan program restorasi rawa gambut dan mangrove. Dalam hal ini mereka dapat mengambil peranan dalam kegiatan restorasi budaya.
Kegiatannya misalnya, menghidupkan kembali tradisi kuliner, obat-obatan, kerajinan, seni, yang erat kaitannya dengan alam. Tradisi yang akan terus berlangsung atau terjaga selama alam terjaga. Artinya, kegiatan ini tidak semata ekonomi, melainkan juga membangun identitas sebagai manusia yang baik di mata Tuhan dan alam.
Guna membangun kembali tradisi ini, tampaknya perlu dihidupkan atau dikembalikan komunitas adat. Bagi mereka yang sudah kehilangan lahan [hutan] adat, dapat diberikan kembali dengan kepemilikan komunal.
Sementara generasi muda, jelas menjadi subjek dari berbagai pendidikan terkait nilai-nilai yang arif terhadap alam. Pendidikan ini mulai di lembaga pendidikan formal, kelompok kreatif dusun atau desa, hingga pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Terakhir, berbagai situs sejarah dijadikan cagar budaya. Keberadaan situs sejarah ini dapat dijadikan potensi ekonomi dan pendidikan, seperti menjadi wisata pendidikan.
Baca: Perempuan, Purun dan Relasi Gender di Lahan Gambut

***
Mungkin tulisan ini terlalu sederhana, dan butuh kajian lebih mendalam, terutama terkait pendekatan atau strateginya dalam menjalankan restorasi budaya. Tapi, semoga niat untuk menyelamatkan alam dan manusia, agar Bumi ini terus lestari, dapat mendorong kita memberikan berbagai masukan.
Dan, selanjutnya, dalam melaksanakan restorasi rawa gambut dan mangrove di Indonesia, sebaiknya pemerintah bukan hanya membebankan tanggung jawabnya pada KLHK dan KKP, juga Kemendikbud, serta melibatkan para pegiat budaya, seperti tokoh adat, seniman, budayawan, arkeolog, dan lainnya.
* Taufik Wijaya, jurnalis, penyair dan pekerja seni di komunitas Teater Potlot. Menetap di Palembang, Sumatera Selatan. Tulisan ini opini penulis.








